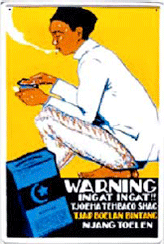Marxisme melihat sejarah sebagai pertentangan antar kelas, dalam hal ini pertentangan antar kelas pemilik modal (kaum borjuis) dengan kelas pekerja (proletar). Artinya, sejarah dalam pandangan marxisme merupakan kenyataan yang dapat diubah, bukan sesuatu yang terberi. Sejarah di sini dilihat sebagai kata kerja, yang menjelaskan bahwa ia dapat dibentuk, dilestarikan, dilawan. Dalam marxisme akan dijumpai gagasan-gagasan seperti hegemoni, kesadaran palsu/ideologi, alienasi (keterasingan). Dalam kepentingan kajian media kiranya ketiga hal tersebut dapat dipergunakan dimana hegemoni menjelaskan bagaimana pihak tertentu patuh terhadap pesan-pesan media tanpa melakukan pembacaan kritis atau secara tidak sadar ia mengamini dan menganggap kepatuhan tersebut sebagai sesuatu yang normal. Kesadaran palsu/ideologi dapat menjelaskan bagaimana tindakan seseorang dipengaruhi oleh gagasan-gagasan tertentu. Pengaruh tersebut bisa berlangsung baik pada proses penciptaan (tindakan) maupun pembacaan. Alienasi kiranya menjelaskan bahwa ada proses pengasingan (ke)diri(an) dalam media.
Kesadaran palsu/ideologi berlangsung misalkan, ketika dalam media terdapat pihak yang menguasai dan terdapat pihak yang dikuasai. Hubungan tersebut menjelaskan adanya dominasi atas pesan-pesan media, di mana umumnya pemilik media dapat mengatur pesan-pesan yang disampaikan. Pesan-pesan media dalam hal ini sudah bukan lagi sebagai kenyataan objektif. Terdapat pihak yang menamai hal tersebut sebagai agenda setting. Misalkan, mengapa sinetron televisi, iklan kecantikan, umumnya menampilkan rumah mewah, mobil mewah, manusia-manusia modern, dikarenakan di balik representasi tersebut terdapat kekuatan modal yang berkepentingan yaitu (konsumsi) kelas dan gaya hidup. Suatu pernyataan Marx menyebutkan bahwa “bukan kesadaran seseorang yang menentukan keberadaannya, namun sebaliknya keberadaan sosial menentukan kesadarannya.” Hal ini terjadi ketika keberadaan sosial sebelumnya telah dibentuk melalui representasi dalam sebuah media, contohnya kesadaran akan kecantikan yang dipertontonkan melalui pemilihan perempuan dengan wujud tertentu, misalkan langsing, putih/kulit cemerlang/bersinar, ngindo, rambut lurus, dll. Sebenarnya, dalam proses yang demikian telah berlangsung proses pengasingan, proses meminggirkan, penyingkiran (alienasi). Rasa minder karena wajah tak (se)cantik seperti pada wajah-wajah perempuan dalam sinetron, mengonsumsi pemutih, mengonsumsi gaya hidup modern, adalah proses-proses yang menunjukkan bahwa menjadi seseorang (being somebody) telah diatur oleh media. Contoh lain, taman makam pahlawan, terutama di kota-kota besar, hampir selalu ditempatkan di tengah kota (tidak di pinggiran). Hal ini digunakan untuk mempertontonkan kepada masyarakat bahwa yang disebut pahlawan ialah orang-orang yang berjasa dalam perang fisik, biasanya menunjuk pada militer. Penempatan yang demikian secara tidak langsung mau mengatakan bahwa keberadaan militer merupakan hal yang wajar, bahwa ia harus ada, harus dihormati, dipatuhi (ingat: konsep dominasi dan hegemoni di atas). Taman makam pahlawan dalam konteks yang demikian menjadi sebuah media yang ingin mengomunikasikan sesuatu. Tentu saja pihak yang menyampaikan pesan tidak lain pemerintahan yang militer(istik).
Seorang teman, Badar, pada sebuah perkuliahan Tinjauan Desain, menanyakan mengapa tak ada (tak hadir) tokoh wayang perempuan dalam iklan Kedaulatan Rakyat? Pertanyaan Badar tersebut bisa menjadi demikian: mengapa yang hadir tokoh-tokoh wayang berkelamin laki-laki? Badar, dalam hal ini, telah berangkat dari sesuatu yang tidak dihadirkan dalam iklan tersebut. Ketidak hadiran tersebut dalam batas tertentu dapat dikatakan bahwa tokoh wayang perempuan di-tiada-kan (tidak dipilih, diasingkan, teralienasi). Jika dikaji seara semiotik, Badar membaca iklan melalui tanda-tanda yang tak hadir (tidak eksis). Hal ini menjadi penting manakala iklan Kedaulatan Rakyat tersebut ternyata bekerja dalam mekanisme gender, bahwa ada suatu gagasan (ideologi) yang memandang bahwa superioritas senantiasa terwakili oleh laki-laki untuk menegaskan sikap-sikap tertentu. (ingat: yang di-tiada-kan pada iklan tersebut bukan sosok perempuan, namun wayang perempuan).
Contoh di atas pun dapat dicari padanan fenomenanya, misalkan (analisis isi) terhadap media-media yang mencitrakan Yogyakarta. Biasanya, Tugu, Prambanan, Kraton, Malioboro, Taman Sari menjadi ikon representatif Jogja, seolah-olah Jogja sebatas hal-hal tersebut. Barangkali pemikiran ini diwarisi oleh cara peng-kelas-an ikon budaya yaitu kraton, alun-alun, malioboro, candi, tugu merupakan lingkungan budaya tinggi (high culture) dan (paling) pantas (untuk) mewakili Jogja. Dalam kata lain, di sana hadir (baca: eksis) suatu kacamata estetika di mana kacamata tersebut didasarkan atas kepatuhan dalam memilih ikon-ikon yang pantas (kesantunan). Jika hal ini berlangsung terus-menerus akan melahirkan pengetahuan di mana pengetahuan tersebut (sebenarnya) menjadi suatu kesadaran palsu/suatu kenormalan/kebiasaan (naturalisasi). Hegemoni hadir dan menegaskan fenomena tersebut salah satunya melalui cara misalkan pendidikan, bahwa dalam proses pendidikan diajarkan bahwa yang di jalanan adalah yang tidak/kurang santun (maka kita mengenal adanya budaya jalanan, untuk membedakan budaya yang bukan jalanan misalkan budaya ruang kelas, budaya kraton, budaya mall). Maka tak aneh kalau istilah street art tidak lahir dari negara kita karena di negara kita yang berada di jalanan dianggap tidak/kurang pantas. Bahkan makna jalan pada masa Orde Baru merupakan ruang yang mesti diwapadai (ingat: tragedi Petrus/Penembak Misterius, di sini (rezim Orde Baru melalui kekuatan militer) dipilih metode tontonan sebagai cara berkomunikasi kepada masyarakat yaitu dengan cara membiarkan mayat gali/preman tergeletak di jalan sebagai bentuk peng-ingat-an). Aneh pula mengapa lebih dikenal julukan seniman Malioboro, bukan seniman jalanan, seolah-oleh gagasan Malioboro mesti digunakan (dipinjam) untuk melegitimasi bahwa dia seorang seniman jalanan yang pantas. Di sini Malioboro beralih fungsi dari sebuah jalan(an) menjadi kepantasan. Dalam bahasa marxis, di sini telah berlangsung proses komodifikasi alias ada pertukaran nilai antara maliboro – jalanan – seniman. Bahwa kalau mau menjadi seniman jalanan ya jadilah seniman malioboro, seolah seniman yang (meng)ada di jalan(an) yang lain bukan seniman. Meski demikian, saat ini beberapa pihak melihat bahwa budaya jalanan pun tak harus diperbandingkan dengan budaya bukan jalanan. Bahwa masing-masing tempat (jalanan, kraton, kampus) melahirkan kelas-kelas tersendiri yang tak perlu dipertentangkan. Sikap seniman kampus yang mengerjakan gagasan di jalanan (mural) dapat dilihat dalam berbagai sisi, (1) intervensi mereka terhadap ruang publik, (2) memindahkan proses pendidikan di kampus ke luar kampus agar seni tak lepas dari kenyataan sosial (seni merupakan bagian dari dunia sosial).
Contoh-contoh di atas masih terjadi hingga kini. Misalkan, dalam pembuatan iklan kita masih menunjuk/mencari referensi iklan-iklan dengan modal besar (iklan televisi, iklan majalah, iklan koran). Padahal, budaya beriklan merupakan kenyataan sehari-hari di mana di sekitar kita terdapat ekspresi-ekspresi iklan yang berbeda (namun belum “dianggap” sebagai sebuah iklan). Hegemoni berlangsung ketika dalam buku-buku tentang iklan, kuliah-kuliah periklanan, menjelaskan bahwa yang disebut iklan adalah iklan seperti yang terdapat pada media televisi, surat kabar, maupun majalah. Sedangkan, selebaran-selebaran, poster-poster di tembok gang kampung, pasar, dll. belum (bisa) dianggap sebagai iklan. Hal ini menjelaskan bahwa diam-diam telah berlangsung kesepakatan bahwa antara pendidikan dan pemilik modal (klien, pemilik media) berlangsung suatu kuasa dalam mempertahankan dan mengontrol pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan iklan (mana bisa pedagang/produsen kelas bawah membuat iklan seperti pedagang/produsen kelas atas). Maka tak aneh kalau gaji desainer di perusahaan periklanan tergolong besar karena memang dibayar oleh klien besar. Sebenarnya, yang dibayar bukan nilai kreativitas, namun bagaimana di sana berlangsung suatu mekanisme dalam mempertahankan (kuasa) pengetahuan bahwa iklan seharusnya demikian. Bayangkan kalau semua klien adalah orang-orang seperti Hitler, atau para ulama, budayawan, atau orang-orang sejenis Thukul Arwana, pengetahuan iklan yang bagaimana yang berlangsung? Hal ini pun bisa menjelaskan kalau obrolan tentang iklan di sebuah kampus filsafat misalkan kurang laku dibandingkan jika obrolan tersebut dilangsungkan di sebuah kampus desain. Atau ngomongin iklan dari sisi etika/moral kurang menarik perhatian dibanding ngomongin iklan dari sisi kreativitas dan peluangpeluang masa depan (gaji, jabatan, dll.). Ini menjadi penting manakala sebuah pengetahuan tentang iklan seharusnya diintervensi oleh beragam kepentingan (mewakili kepentingan banyak pihak). Jadi, jika iklan masih mengumandangkan seputar tubuh-tubuh eksotis/erotis, hal itu tak aneh karena erotisme/eksotisme tubuh tak perlu diomongin di kampus kreatif tapi di kampus yang memang mengurusi hal tersebut (filsafat, etika, agama, dll.).
Marxisme, bagi saya, menyediakan sebuah pisau tajam dalam memandang hadirnya kuasa dalam media. Dengan kesadaran seperti ini teks media bukan lagi sebagai suatu kenyataan yang objektif, bahwa di sana telah hadir beragam kepentingan. Barangkali pula kita tak tahu bahwa kita turut ambil bagian dalam pelestarian kuasa tersebut. Mengapa? Bisa jadi karena kita tak mau tahu, atau selama ini kita telah terhegemoni, atau tak menyadarinya sebagai suatu ketidakwajaran. Marxisme, meski makin tua usianya, namun dia tetap relevan dalam menilai sikap media bagi kita, baik sebagai pembaca maupun sebagai kreator. “Sesuatu yang nampak wajar belum tentu merupakan sebuah kewajaran”. Marxisme mengajak kita untuk senantiasa kritis dan melawan. Belajar dari pengalaman Badar bahwa kita mulai melihat dan memikirkan melalui apa-apa yang tak dihadirkan. Barangkali ketidakpenghadiran tersebut menjelaskan banyak hal penting dalam menilai kedirian kita selama ini, terutama yang dipengaruhi (dibentuk) oleh dan dalam media.
Iklan enamel Roko Prijaji di atas merupakan sebuah usaha bagaimana rokok diarfirmasi oleh masyarakat. Di sana hadir sebuah praktik peminjaman, yaitu diperlukan sosok/figur tertentu dalam menegaskan (budaya) merokok. Lebih lanjutnya bahwa rokok pun seperti lapisan dalam masyarakat, bahwa di sana terdapat kelas-kelas dalam rokok. Pada saat yang sama si rokok tersebut tak perlu memikirkan apakah rokoknya akan dikonsumsi kaum priyayi atau masyarkat lapis bawah. Pada saat kelas priyayi menegaskan dirinya melalui simbol-simbol tertentu (Roko Prijaji), pada saat yang sama kelas bawah berusaha menjadi priyayi dengan mengonsumsi rokok sang priyayi tersebut, seolah sudah seperti priyayi (menjadi priyayi/becoming priyayi). Kebutuhan merokok menjadi kebutuhan sekunder, kebutuhan menjadi priyayi menjadi kebutuhan primer. Di sinilah hebatnya iklan, bahwa dia mampu menyediakan proses to become somebody else. Proses inilah yang dinamakan alienasi.
Sama halnya dengan tembakau Tjap Boelan Bintang. Pada iklan enamel di atas memperlihatkan kepada kita bahwa pemilihan figur tertentu, yaitu dengan simbol yang identik dengan pakaian muslim Abangan (peci, sarung, kemeja) digunakan untuk menegaskan budaya merokok. Iklan di atas mesti dilihat perbedaannya dengan iklan Roko Prijaji, di mana pada iklan Roko Prijaji tidak dihadirkan simbol-simbol keagamaan, namun simbol kelas kebangsawanan. Seseorang akan mengidentifikasikan dirinya apakah ia akan merokok Tjap Boelan Bintang atau Roko Prijaji. Kehebatan iklan bukan terletak pada sisi penggarapan (craftmanship) namun pada usaha dalam memberikan pilihan kepada masyarakat prosesproses pengidentifikasian diri melalui simbol-simbol dalam iklan tersebut. Bukan aku merokok, namun aku merokok seperti yang dipertontonkan dalam iklan.
Dua buah iklan enamel di atas bisa menjelaskan bahwa iklan mampu menciptakan suatu kebutuhan tertentu bagi konsumen, yaitu bukan pada kebutuhan merokok namun merokok agar seperti yang terimajinasikan dalam iklan tersebut. Analisis Marxis berusaha menjelaskan bahwa semua hal tersebut telah diatur. Kesadaran bahwa aku merokok telah diatur oleh suatu mekanisme tertentu, yaitu iklan. Di samping itu, melalui iklan-iklan tersebut, budaya merokok berusaha dalam memperoleh sikap-sikap penerimaan dalam masyarakat: bangsawan maupun kaum agamawan pun merokok. Di sini telah hadir mekanisme legitimasi maupun normalisasi, bahwa merokok itu hal yang wajar dan boleh-boleh saja. Melalui priyayi, rokok (seolah) memperoleh tempat sebagai produk berkelas (high culture). Melalui sosok agamawan rokok (seolah) memperoleh tempat bahwa dia tidak bertentangan dengan ajaran agama.
Saya kira, yang menjadi media pada iklan-iklan di atas adalah sang priyayi dan sang santri (the medium is the message). Mudahnya, untuk mengatakan bahwa merokok tidak merusak kesehatan tak perlu dengan cara memberi bukti-bukti analisis kesehatan, cukuplah dengan memberi bukti bahwa ada juga dokter yang merokok (dokter menjadi the medium yang mengandung message tertentu). Mengapa? Karena dokter dalam dunia sosial diberikan suatu kesadaran tertentu, yaitu bahwa dia berurusan/kompeten dalam hal kesehatan.
Tulisan ini digunakan sebagai bahan ajar mata kuliah pilihan Kajian Media di DKV ISI Jogja yang diajar oleh penulis.
Quoted
“Seorang desainer harus memiliki keberpihakan pada konteks membangun manusia Indonesia. Peka, tanggap, berwawasan, komunikatif adalah modal menjadikan desainnya sebagai alat perubahan”