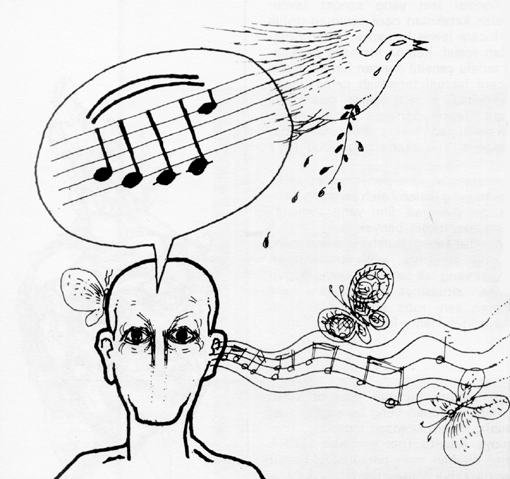Gelombang perkembangan seni rupa Indonesia memasuki daerah pijak baru dalam tiga tahun terakhir ini 1974-1977). Dan ini dianggap oleh sementara orang sebagai gerak perubahan manifestasi yang bukan saja fisik tapi juga konsep secara besar-besaran. Dan bahkan ada yang mengangkatnya sebagai sebuah denyutan yang lebih besar denyutnya daripada gembor Persagi dulu yang ditokohi oleh S. Sudjojono dan Agus Djaja, di kurun tahun 1938.
Mengapa tidak, jika dulu Sudjojono mengumandangkan bahwa seni lukis harus dikembalikan sebagai medium ekspresi secara tuntas dari seorang pencipta dan hasil seni adalah “jiwa ketok” {jiwa nampak) — “Hij is de vinger afdruk van de dief” katanya, maka sekarang jauh lebih kompleks dari itu.
Tokoh-tokoh muda dengan tidak meninggalkan “jiwa ketok” — yang secara implisit sudah berada dalam sebuah karya cipta — telah mendobrak ketertutupan karya seni.
Egoisme, elitisme dan mitos tentang seni yang bermula dari “keterlanjuran” dibabat. Tokoh-tokoh muda ini memanahkan semboyan ke segala penjuru.
Seni rupa — katanya — haruslah lebih menyuarakan lingkungannya, masyarakatnya. Mereka dituntut untuk menjadi reflektor jamannya. Bahkan sebagai “Antennace of Society” seperti yang dikatakan McLuhan. Seniman sebagai penerima getaran-getaran dari masyarakat. Dia bisa berfungsi sebagai tabib dari masyarakat. Ia pendeta. atau bahkan yang akan bicara tentang segala sesuatu yang akan terjadi dalam masyarakat.
Dan rupanya juga, tokoh-tokoh muda ini tak lagi berhubungan dan barurusan dengan apa yang dinamakan “keabadian karya”. Dilihat dari karya-karya yang dipamerkan, nampak sikap momentik, walaupun tak seluruhnya. Seperti halnya sebuah teater, karya mereka hanya menempelkan suatu kenangan yang berat di dahi kita. Yang kemudian ditendang dalam sebuah proses persepsi. Mendera dan meluruskan jalan hidup manusia.
Pandangan bahwa karya cipta yang menggantung di tembok tak memiliki kemampuan untuk mengubah sebuah tatanan kehidupan (oleh karena terlampau terlibat pada perhiasan dan pemilikan pribadi) juga tercantum pada percik konsep mereka.
Karya cipta yang tak melibatkan lingkungan — dengan subject-matter yang terlampau khusus — mereka sebut seni onani.
Tokoh-tokoh muda yang bekerja dengan semangat muda, dengan hasil manifestasi yang cerah dan segar itu, telah resmi memanggul nama yang sekedar sebagai predikat: “Grup Seni Rupa Baru”. Sebuah kelompok yang kebanyakan terdiri dari pelukis dan pematung. Sebuah kelompok yang bukan sekedar mencari kelainan, tapi karena dituntut oleh pertumbuhan jaman, atau gelombang situasi.
Bambang Budjono, kritikus seni rupa, mencatat bahwa Seni Rupa Baru telah mengembalikan semangat bermain seorang seniman. Naluri untuk bergurau dalam sebuah proses penciptaan, sanggup menjulurkan suasana renyah dan segar dalam karya-cipta. Gurau tapi serius.
Belum panjang perjalanan Seni Rupa Baru tersebut. Namun telah menjalin suatu runtunan perkembangan yang menggembirakan (Tentu saja jika mau meniliknya tanpa suatu sikap apriori, tanpa nafsu menutup mata untuk menilik prospek mereka).
Di tengah-tengah tahun 1974 sebenarnya telah nampak hadirnya gejala akan munculnya “agresor-agresor” dogma-seni lukis. Pagelaran Bonyong Munni Ardhi, Harsono dan Nanik Mirna akhir tahun 1974 barangkali merupakan awal dari pertumbuhan ini, meskipun tak bolah diabaikan manifestasi yang serupa telah juga tumbuh pada baberapa akademi seni rupa lainnya, ITB misalnya. Namun karya-karya mereka tak sampai pada tingkat pagelaran.
Seni lukis yang mendobrak bingkai empat sisi dan lantas menjadi sebuah toalet yang berdiri, dengan menyiratkan multiinterpretasi dan sekian simbol, adalah suatu perkembangan yang menggembirakan.
Awal dari pertikaian pendapat soal ini pecah di ujung tahun 1974. ketika Dewan Juri Pameran Besar Seni Lukis Indonesia mensahkan karya-karya A.D. Pirous, Aming Prayitno, Widayat, Irsam dan Abas Alibasyah sebagai karya terbaik. Bahwa karya-karya dekoratif dan “konsumtif” ini terpilih. agaknya tak terlalu menjadi soal. Tapi kalau ada pendapat bahwa dibutuhkan karya-karya yang Indonesiawi dengan menampik karya-karya yang sifatnya eksperimental, maka hal itu menjadi masalah.
Masalahnya menjadi besar, bila ternyata yang menampik justru orang-orang yang memegang “kekuasaan” kesenian. yang kebetulan diberi hak untuk memegang kendali. Hingga muncullah sebuah karangan bunga yang bertuliskan: “Ikut berduka cita atas kematian seni lukis Indonesia” yang dikirimkan ketika para “pelukis terbaik” itu menerima hadiahnya. Bersamaan dengan itu sebuah statement disebarkan dengan nama “Desember Hitam” yang mengemukakan harapan agar pengayom seni rupa menjamin keanekaragaman seni rupa di Indonesia, tertabur dalam momen yang sama.
Peristiwa ini belum selesai, di Sekolah Tinggi Seni Rupa ASRI Yogya terjadi pertikaian lanjutan, kini antara kebijaksanaan dosen atas beberapa mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa Harsono, B. Munni Ardhi, Ris Purwana dan Hardi, yang ikut menandatangani Statement Desember Hitam, diskors tanpa batas, dengan tuduhan-tuduhan politis yang tak jelas. Beberapa dosen yang membela juga terkena sanksi “dikeluarkan”. Sementara itu bisa dicatat, mahasiswa ITB dan LPKJ yang. ikut menandatangani statement tersebut tak mendapat sanksi apa-apa. Lembar “Desember Hitam” bahkan mendapat tempat di dinding-dinding sekolah mereka.
Penskorsan tanpa batas tersebut, mestilah menimbulkan suasana depresif. Tidak saja pada mereka yang terkena langsung, namun juga mereka yang memiliki naluri kreatif yang sama. Sesuatu yang tadinya akan dijalankan secara formal dan prosedural jadi teracak-acak oleh berbagai tekanan. Sekelompok golongan dengan sengaja mendalihkan politik dan menyudutkan tokoh-tokoh muda pada tindakan anarkhi. Pagelaran sudah tidak lagi ditanggapi dengan hati dan kunci-kunci kesenian. Maka dari situ terjadilah “Pemberontakan Seni”. Dari kelompok muda timbul sikap mempertahankan diri sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip keseniannya.
Pemberontakan terjadi tidak hanya pada mereka yang tertindas dan sengaja dikotakkan, tapi juga terjadi pada mereka yang menyaksikan penindasan itu, di mana orang lain yang menjadi; korban. Barangkali dari itulah muncul pameran “Nusantara-Nusantara” (Berlangsung di Karta Pustaka Yogya). Yang mengharapkan keterbukaan pamong-pamong seni terhadap perkembangan yang wajar, dan menolak pendiktean gaya seni.
Dari sini bisa disimpulkan ada keresahan yang dikandung sudah cukup lama, sehingga pelukis-pelukis muda: Samikun, I Gusti Bagus Widjaja. Wardoyo, Kristianto, Sudarisman, Suatmadji, Agustinus Sumargo, Agus Dermawan T. menggelarkan lukisan-Iukisan sindiran dalam pameran “Nusantara-Nusantara” itu. Pagelaran ini berakhir dengan tragis, ketika terdengar isyu bahwa mereka yang berpameran akan mendapat sanksi berat dari sekolahnya ASRI. Di suatu pagi buta ketujuh dari mereka membuat pernyataan maaf pada direktur sekolah sambil melimpahkan tanggung jawab pada seorang saja: Agus Dermawan T. Perkara dengan mudah selesai. Nama yang mendapat beban tersebut secara tak langsung dikeluarkan dari Sekolah Tinggi Seni Rupa ASRI.
Pameran Seni Rupa Baru 75 adaIah perwujudan cita kaum pemberontak seni yang pertama. Ini berlangsung bulan Agustus ’75. Waktu itu di TIM muncul: Anyool Subroto, Bachtiar Zainoel, Pandu Sudewo, Nanik Mirna, Muryoto Hartoyo, Harsono, B. Munni Ardhi, Hardi, Ris Purwana. Siti Adyati dan Jim Supangkat. Dengan begitu, karya-karya bombas dan bersemangat secara resmi masuk ke dalam kancah seni rupa Indonesia. Sanento Yuliman berkomentar dalam satu nada bertanya: “Dapatkah kita katakan, bahwa dalam pameran ini kita sedang diperkenalkan kepada pengalaman kesenian yang baru, di mana perasaan akan kekongkretan merupakan aspek dasar yang meresapi kwalitas pengalaman itu, menyebabkan pengalaman ini berbeda secara kwalitatif dengan pengalaman kesenian yang konvensional?” Satu nada yang menyodorkan masalah. Sebuah cara yang lebih baik dan bijaksana daripada memberikan penjelasan-penjelasan yang sifatnya agitatif.
Di Yogya, Agustus ’76 Tulus Warsito dan Budi Sulistyo membeberkan karya yang mereka sebut “Esensialisme Pop Art”. Perwujudan yang mirip dengan manifestasi Seni Rupa Baru.
Dan sebuah peristiwa unik iagi yang dicetuskan orang-orang Seni Rupa Baru, adalah Pameran Konsep. Ini terjadi di Balai Budaya Jakarta tahun 1976. Corat-coret buah pikiran digelarkan. Sebuah aktivitas intelektual yang menarik. Peristiwa tersebut seolah menyarankan, bahwa mereka tidak hanya berdiri dengan kaki, tapi juga dengan otak.
Sementara itu, efek bentuk dari gerakan Seni Rupa Baru mulai menjalar, dan efek konsepnya mulai menular. Seni dengan libatan sosial, seni yang dekat dengan lingkungan, seni yang menolak spesialisasi, seni dengan semangat berkomunikasi, seni yang kembali pada rakyat, seni yang menganggap “seni dahulu” sebagai bahan baku snobisme, seni yang dituntut untuk didukung oleh pikiran-pikiran jenial. dan seni yang tak lepas dari gairah bereksperimen.
Hal tersebut agaknya telah tercanang pengaruhnya di beberapa sanggar remaja di Jakarta. Bahkan konon juga masuk dalam kurikulum Departemen Seni Rupa ITB sebagai mata pelajaran baru.
Pameran Seni Rupa Baru yang kedua berlangsung Februari/Maret 1977. Persoalannya menjadi lebih jelas. Gelombang krisis moral dan estetis yang dituduhkan beberapa pelukis tua tertimpali dengan karya-karya positif, menarik, bermutu dan meyakinkan. Yang hadir bukan lagi karya depresif, namun karya yang menunjukkan masa depan yang melebar. Meruak cakrawala baru. Menyodorkan kemungkinan-kemungkinan. Pameran ini selain diikuti oleh gembong-gembong yang terdahulu juga diikuti oleh sejumiah peserta baru: S. Prinka, Ronald Manulang, Satyagraha, Nyoman Nuarta, Wagiono, Dede Eri Supriya. Mereka datang dari Bandung, Yogya dan Jakarta.
Pameran seni “Kepribadian Apa” yang berlangsung di Yogya September ’77 agaknya masih getol mengorek kasus lama. Menolak pemantaban konsep mentah “mempribadikan karya-karya seni Indonesia”. Seni dalam keberaturannya mengharapkan kebebasan yang lebih luas. Tanpa mau dibatasi benteng-benteng tangan yang berwenang, yang justru dianggap tak peka terhadap getar kesenian. Pagelaran yang mirip “happening” itu dilkuti oleh pemusik Sapto dan Jack Body. Dan seni rupawan-seni rupawan: Dede, Gendut Riyanto, Wienardi, Tulus Warsito, Budi Sulistyo, B. Munni Ardhi. Haris Purnama, Slamet Ryadi, Redha Sorana dan Ronald Manulang. Pameran ini ditutup polisi pada hari kedua. Sebabnya kurang jelas.
Dalam Pameran Pelukis Muda Indonesia ’77 bulan Desember, gaya “Seni Rupa Baru” nampak mendominir ruangan, muncul karya-karya tiga dimensional. Walaupun dalam kriterium tertulis bahwa yang bisa digelarkan terbatas pada karya dua dimensional. Dan nyatanya pelukis-pelukis muda pada pameran ini tidak mengacuhkannya.
Sementara itu, di balik layar pentas lakon “penerobosan” kaidah-kaidah seni lukis konvensional pelukis-pelukis tua seperti Nashar, Rusli, Popo Iskandar, Bagong Kusudiardjo, Kusnadi, Oesman Effendi, Fadjar Sidik, A. Sadali, Suparto, Umi Dachlan, Affandi, Amri Yahya, tetap bekerja dengan gaya yang sudah bertahun-tahun dirintisnya. Ada beberapa yang menampakkan kemajuan, namun lebih banyak yang terjun dalam kemunduran. Masih ada dari mereka yang terus bersitegang dengan idealisme “seni murni” nya tapi sebagian yang lain sibuk dengan urusan bisnis seninya. Yang mandul, bahkan bermain-main dengan kekuasaan untuk mengatur-atur dan menindas.
Sedang pada pelukis-pelukis muda yang tetap bertahan pada “visi lama” ada juga yang menampakkan kemajuan-kemajuan teknis, namun tetap sepi dan bungkam, jika menyinggung soal prinsip dan konsep, bahkan aktivitas pameran tak ada pada mereka. hingga sulit untuk mencari apa yang perlu dicatat dari mereka, sebab seolah-olah mereka telah mundur dari percaturan seni rupa.
Ini semua catatan saya sebelum tahun 1978. Siapa tahu, pada tahun genap dan seterusnya ada pergolakan yang lebih seru. Siapa tahu.
Sumber: Buku Kumpulan Karangan “Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia”, editor: Jim Supangkat, penerbit: PT Gramedia, Jakarta 1979, halaman 1 s/d 4.
Quoted
Desain (grafis) adalah kata kerja–bukan kata benda–karena mengutamakan proses; berupa pengolahan nilai keunikan dan keotentikan dari suatu problem