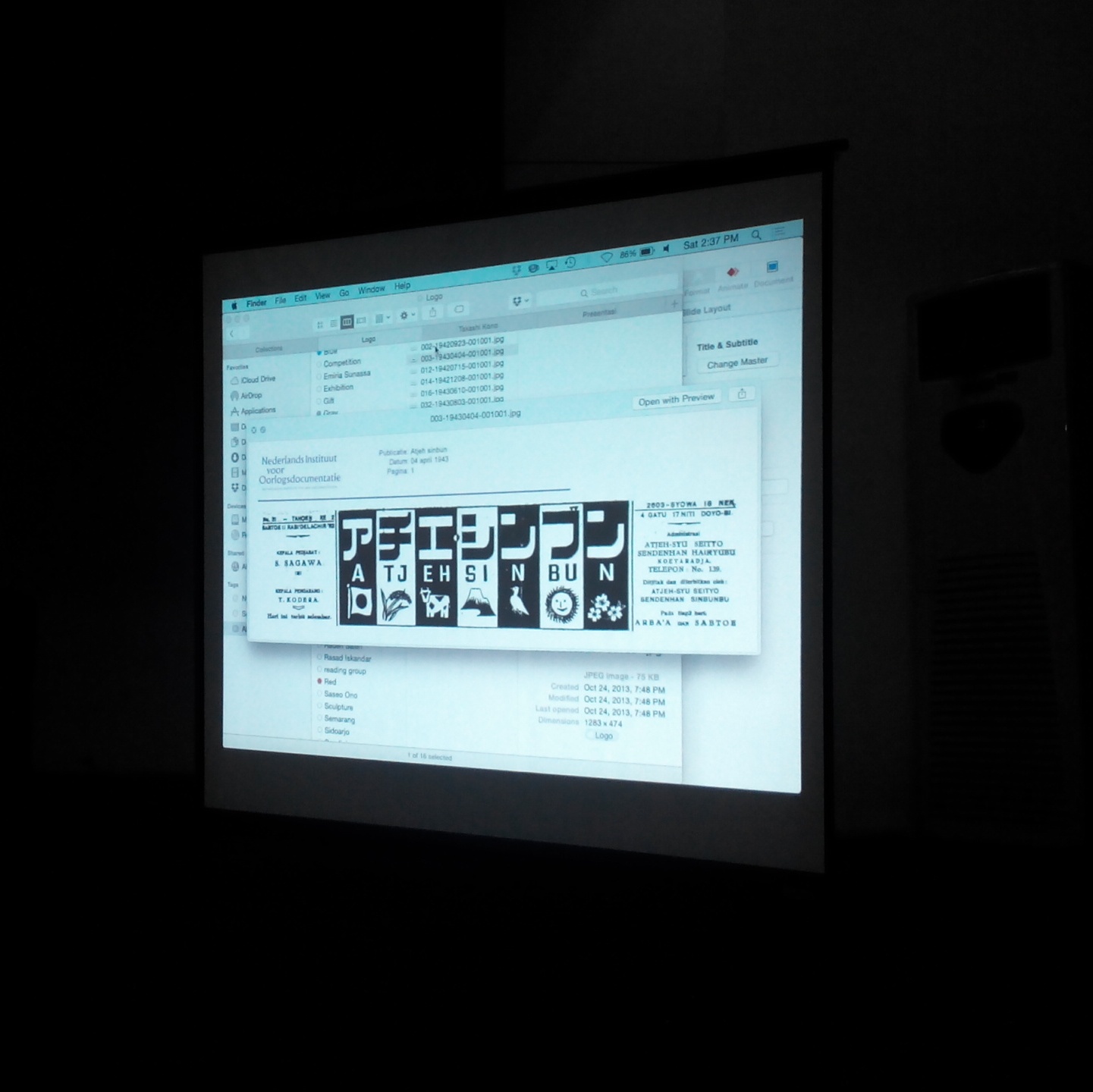“Ada tiga penyakit paling berbahaya jika kamu datang ke Indonesia,” pesan seorang prajurit Nippon pada mereka yang hendak diberangkatkan ke Indonesia, “Yakni (demam berdarah) dengue, malaria, dan Ono Saseo. Dari ketiganya, yang terakhirlah yang paling mematikan.”
Tak pelak, gelak tawa mengisi Ruang Auditorium Gedung Rektorat Institut Kesenian Jakarta pada Sabtu, 13 Juni 2015 lalu. Ingatan A.D. Pirous akan seniman berkacamata dan berperawakan jenaka itu pun memperkaya sesi diskusi dalam seminar bertajuk GURAFIKU 1942-1945: Nippon, Asia Timur Raya, dan Praktik Desain di Indonesia.
Maret 1942. Dalam kecamuk Perang Dunia II, Jepang menginjakkan kakinya di Jawa. Tak hanya prajurit militer, seniman juga turut dalam rombongan. Sebagaimana Aiko Kurasawa pernah mencatat dalam bukunya Mobilisasi dan Kontrol (1993), keterlibatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan operasi militer menjadi sasaran utama yang harus digerakkan. Dengan struktur yang kompleks dan lengkap, propaganda pun jadi amunisinya. “Jepang saudara jauh Asia”, katanya. Seniman, karenanya, turut memegang peranan yang tak kalah penting dalam operasi militer ini. Dengan daya panggil yang dimilikinya, propaganda yang bertujuan untuk mobilisasi ini lebih dari sekedar alat manipulasi. Ia dimaksudkan juga untuk mematahkan dominasi kultural.
Keterlibatan seniman Jepang dalam era penting dalam sejarah republik itu pun menyisakan pula penggalan penting yang membentuk praktik seni rupa di Indonesia. Menggali kembali akan praktik seni rupa dan kolektivismenya pada era tersebut, Antariksa, seorang peneliti kebudayaan dari KUNCI Cultural Studies Center merampungkan sebuah penelitian akan praktik seni rupa di Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Dalam GURAFIKU 1942-1945, Antariksa menghadirkan cuplikan penelitiannya dengan paparan akan aspek khusus dari masa itu: desain grafis. Bersama Hilmar Farid, sejarawan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Antariksa membawa hadirin menelusuri kembali praktik seni dan grafis di bawah mobilisasi Jepang dan keterkaitannya dengan aspek sosial-politik masa itu, serta relasinya dengan sejarah seni rupa dan grafis di Indonesia.
Mengawali presentasi dengan kilasan akan penelitiannya di Jepang, paparan Antariksa mengerucut pada nama Ono Saseo dan Takashi Kono—dua dari sekian seniman kawakan Jepang yang turut diterjunkan dalam sepak terjang operasi militer Jepang di Indonesia. Ono Saseo, seorang kartunis yang pada dekade 1920-an lebih banyak menggambar komik-komik seksual Jepang, turut diterpa gelombang nasionalisme Jepang di tahun 1930-an hingga gambar-gambarnya pun sarat politis. Pada 1942, ia diberangkatkan ke Indonesia. Tiga hari setelah kedatangannya di tanah Jawa, Ono Saseo menggambar mural di rumah penduduk di Banten—yang menjadi mural tertua di Indonesia.
Sementara itu, dikenal dengan sebutan ‘ahli reklame’, ‘tukang lukis’, atau ‘tukang gambar’, sejarah desainer grafis di Indonesia pada masa itu sedikit banyak berada di bawah kiblat Takashi Kono. Pada periode tersebut, Takashi Kono telah dikenal sebagai desainer grafis modern Jepang yang penting dan berpengaruh. Menjabat sebagai Ketua Departemen Seni Rupa Keimin Bunka Shidoso, pencetus Manifesto Seni Rupa ini memegang peranan penting dalam propaganda di Indonesia melalui berbagai arahan rancang grafis yang dilakukannya.
Sebagai Supervisor, Kono yang memang aktif mendesain sepanjang 1906 hingga 1999 ini menjadi tokoh yang mempengaruhi gaya grafis kala itu. Memperkenalkan teknik montase dalam eksekusi tata letak di Indonesia, perwajahan majalah Djawa Baroe pun turut dipengaruhinya. Karya-karya Kono sendiri masih banyak tersimpan rapi di negaranya, sedang beberapa desain lainnya yang disimpan di Belanda.
Mencermati praktik seni rupa dan grafis yang tak dapat lepas dari konteks sosial dan politiknya, praktik seni rupa dan grafis pada tahun-tahun terakhir penjajahan republik ini telah menjadi waktu yang begitu penting. Indonesia menjadi kasus yang unik bila dibandingkan dengan jajahan Jepang lainnya di era yang sama. Tujuan mobilisasi dan kontrol lewat berbagai organisasi bentukan yang ternyata bersambut di Indonesia telah menghadirkan pula relasi yang bersahutan antara seniman Jepang dan Indonesia. Dalam konteks desain grafis, sebutlah Iton Lesmana yang menjadi pentolan dalam Keimin Bunka Shidoso, mengisi daftar sosok desainer di zaman penjajahan yang menjadi pelopor dan pengaruhnya terhadap desain grafis Indonesia. Sayangnya, ia luput dari pencatatan sejarah, sebagaimana jejak Kono di Indonesia yang terhenti begitu Jepang kalah perang.
Begitu kayanya aspek-aspek yang saling terkait dalam tuturan Antariksa dan Hilmar Farid lewat diskusi yang dimoderasi Iwan Gunawan siang itu sekiranya menjadi sebuah tepukan di pundak. Ketika Saseo Ono dan tarikan-tarikan garisnya menurun dan berlanjut menjadi bagian dari sejarah seni rupa Indonesia, peran Takashi Kono dan sejarah desain grafis di Indonesia sesudahnya kehilangan jembatan penghubung. Ketika seni rupa telah memiliki gerakan yang ajek—jika tak bisa kita sebut mapan—hingga potongan-potongan sejarahnya membentuk keterkaitan untuk membangun pemahaman yang padat, sejarah rancang grafis meluangkan sebuah ruang kosong. Tanpa keharusan pembuktian akan kontinuitas dalam praktiknya, hal ini sekiranya menjadi sebuah peluang bagi peneliti untuk menelusuri, mendokumentasi, dan menelaah sosok dan karya-karya perancang grafis era-era krusial di Indonesia lebih jauh lagi.
Gurafiku 1942-1945: Nippon, Asia Timur Raya, dan Praktik Desain di Indonesia diselenggarakan oleh Desain Grafis Indonesia dengan dukungan dari Dewan Kesenian Jakarta dan Institut Kesenian Jakarta.
Tentang Gurafiku 1942-1945 | Dokumentasi Audio Gurafiku 1942-1945
Quoted
“Keberhasilan merancang logo banyak dikaitkan sebagai misteri, intuisi, bakat alami, “hoki” bahkan wangsit hingga fengshui. Tetapi saya pribadi percaya campur tangan Tuhan dalam pekerjaan tangan kita sebagai desainer adalah misteri yang layak menjadi renungan.”