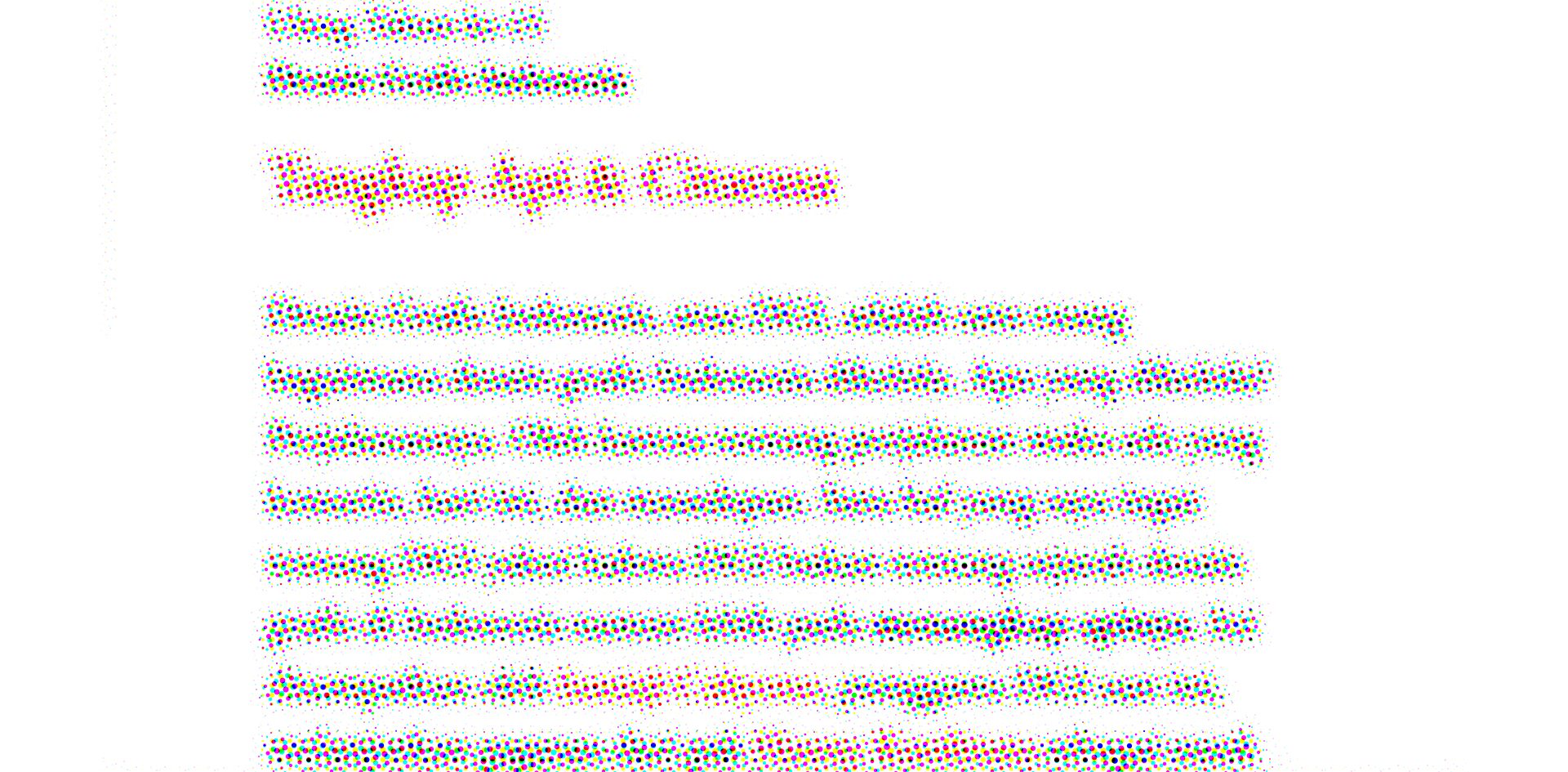
Desain Grafis Indonesia, atau DGI, adalah satu ruang bagaimana desain grafis Indonesia dikelola. Apa yang dikelola? Perjalanannya. Oleh karena tentang perjalanan maka ada yang kemarin, hari ini, dan masadepan. Satu hal yang saya ingat tentang DGI yakni bahwa DGI bukan tentang sejarah desain grafis di Indonesia namun lebih pada menangkap apinya. Ini disampaikan oleh Ismiaji Cahyono, punggawa DGI saat ini, melanjutkan gagasan dari pak Hanny Kardinata sebagai sosok penting adanya DGI.
Saya sependapat dengan menangkap api, dan dalam ulang tahun ke-15 DGI saya mau berbagi gagasan bahwa selain menangkap api sejarah DGI juga menjadi ruang mengelola citarasa desain grafis Indonesia.
Perjumpaan pertama saya dengan DGI yakni sewaktu interface situs DGI masih bernuansa hitam. Kesan bidang hitam tersebut masih dipertahankan di situs yang beroperasi saat ini hanya saja untuk bagian membaca artikel terasa lebih nyaman, latar bidang terang dengan teks gelap.
Beberapa artikel di yang diunggah di DGI saya gunakan untuk mengajar. Misal, artikel tentang kreativitas Sandy Karman sewaktu menjajagi material kertas dengan teknik cukil. Betapa nuansa hati-hati sekaligus kematangan gerak tangan terlihat di situ. Robekan kertas tersebut berhasil memukau saya, memberi impresi yang menggetarkan: kerapuhan kertas justru menjadi kekuatannya. Itulah estetika, yang kian kuat hadir dengan pilihan simbol gambar para pahlawan nasional.
Artikel lain, “Spacebar: Skuter Listrik Kolaborasi Katalis dan Kamengski, Kecil tapi Menggigit” bagi saya menyajikan inovasi kerja kolaborasi sebagai bentuk kerja desain hari ini.
Dan berbagai artikel lainnya.
Kadang di beberapa artikel terdapat argumen yang kurang selaras dengan pemikiran saya. Tapi itu tidak menjadi masalah, lagipula tulisan-tulisan saya di DGI pun sangat mungkin demikian di hadapan para pembaca. Perbedaan argumen tadi saya sikapi dengan cara mengubah posisi saya pembaca membayangkan dalam posisi diayangmenulis. Dalam beberapa kesempatan hal tersebut berhasil memunculkan pengetahuan baru bagi saya pembaca. Boleh jadi nuansa desain grafis dalam pengertian cetak masih kental mewarnai berbagai imaji dalam situs DGI. Namun, ulasan tentang skuter listrik, dan berbagai percakapan lainnya tentang pembelajaran desain grafis, sisi politik desain grafis, sejarah lembaga, sosok dan tokoh desain grafis memerlihatkan bahwa DGI adalah tentang dinamika desain grafis yang tak sebatas tentang cetak atau digital, atau virtual, tetapi ragam sisi tentang desain grafis.
Lantas, bagaimana saya belajar tentang citarasa desain grafis dengan situasi saya saat ini yakni di Jogja?
Kota ini, khususnya para penerbit buku dan para perupanya telah meluluskan saya menempuh pendidikan studi lanjut desain. Saya boleh berhutang banyak pada para penggerak perbukuan di Jogja tersebut.
Di sisi lain generasi baru senantiasa hadir. Tren bergerak.
Demikian dengan desain perbukuan di Jogja. Desain-desain lama (gaya lawasan) masih ada yang menerapkannya, dengan hasil yang baik. Desain-desain bernuansa berbeda/baru juga hadir dengan hasil yang juga baik.
Jika saya ditanya “bagaimana desain buku di Jogja saat ini?, jawaban yang akan saya berikan yaitu, “Saya pernah mengulasnya beberapa tahun yang lalu, hingga kini yang pernah saya ulas tersebut terus berkembang karena wawasan baru yang saya jumpai untuk melihat ulang.” Itulah yang boleh jadi maksud dari “menangkap apinya”.



Seniman (pelukis) menerbitkan kumpulan cerita pendek. Acara perbukuan hadir memberi ragam gelaran. Adakalanya tren bertiup dari Jogja, ada kalanya yang di Jogja ikut tren buku pada umumnya. Sumber:Internet (Maret 2020)
Hadirnya tren baru tidak sama sekali merontokkan apresiasi terhadap tren desain buku sebelumnya yang barangkali telah mendapati ruang heroik dalam ruang yang lebih besar seperti sosial, politik, dan budaya (dari era Orde Baru ke era awal Orde Reformasi).
Desain buku cetak hari ini juga punya tantangan zamannya. Desain buku cetak hari ini melakukan siasat desain dalam menghadapi buku elektronik dan audio book. Satu hal yang kian terjaga yakni sisi kesenirupaan atau desain grafisnya menjalankan peran besar bagi pembaca sejak sampul dan terutama halaman isi. Maka, dibanding bersitegang mana yang lebih baik, buku cetak, buku elektronik, atau audio book lebih bermanfaat menyadari pesan di setiap medium tersebut seperti bagaimana ia digunakan, bagaimana media tersebut memengaruhi kebiasaan kita, dsb. Tantangan zaman inilah yang sedikit banyak membedakan dari desain buku di era sebelumnya. Dan, persoalan besar yang dihadapi buku hari ini yakni godaan berpikir pendek akibat, misal, terpaan teks-teks di internet yang lebih ringkas dan siap santap.
Lantas apa arti Jogja dalam situasi tersebut? Saya rasa Jogja menjadi ruang yang inklusif. Inklusif itulah yang saya rasa juga hadir di DGI. Kita bisa menjumpai ulasan atau desain yang, katakanlah, paling canggih hingga paling sederhana (tapi rumit juga sih). Dari kerasnya material skuter listrik hingga remasan kertas Sandy Karman. Saya rasa adanya visi menangkap api, dan mengelola citarasa menjadikan skuter dan remasan kertas bisa berada di satu ruang yang sama. Singkatnya, DGI semakin siap mengelola keragaman.
Keragaman itulah yang juga saya jumpai di Jogja: keragaman penerbit, keragaman acara perbukuan, keragaman desain buku, keragaman toko buku, keragaman komunitas buku, perpustakaan, pasar buku bekas, keragaman percakapan buku. Tentu, kota atau tempat lain juga memiliki hal-hal tersebut. Memang, di beberapa kesempatan hadir nuansa kurang nyaman seperti perseteruan antar penerbit, hegemoni selera atau tren desain, batasan keikutsertaan pameran, dsb.
Hal-hal seperti ini juga penting karena menunjukkan adanya persoalan dan apa yang sebenarnya menjadi persoalan. Lantas, menjadi seorang desainer grafis tidak cukup mengandalkan kecakapan teknis dan teoritis, tetapi, meminjam idiom saat ini, soft skill. Sebuah kota tidak sebatas tentang kota perbukuan, tetapi juga konflik perbukuan. Kecepatan serta ketepatan menyelesaikan konflik itulah yang membuktikan sebuah kota sebagai kota perbukuan.
Apa yang paling saya syukuri dan berarti dalam perbukuan di Jogja yakni berjumpa dengan para penggeraknya, dengan para pelakunya baik yang sering berada di depan serta yang memilih bekerja di balik meja. Mungkin di situ saya sebagai pendengar saja, sambil menyimak desain-desain terbitan mereka.
Tepat juga pengertian desain grafis yang diajukan oleh kolega pengajar desain di Purwokerto, akrab disapa Dito, “Secara sederhana desain grafis dapat dimengerti sebagai aktivitas yang terletak di beragam persimpangan, yaitu seni visual, komunikasi, dan psikologi, dan orang yang melakukan kerja desain sering disebut sebagai desainer.” (Arsita Pinandita, 2019: 1) Dan, lebih dalam lagi apa yang disampaikan kolega mengajar saya di kampus, guru saya, pak Umar Hadi (kelas Metodologi Desain) bahwa menjadi desainer itu menjadi orang yang tidak tahu apa-apa terutama di era desain dan pengguna, alias rendah hati.
Jika menangkap api, dan mengelola citarasa sudah dijalani, selanjutnya ada tantangan yang lebih besar: kepribadian desain grafis Indonesia. Kepribadian ini akan terus diuji oleh waktu dan perjalanan. Desain boleh berubah, visi bisa kembali diolah, tren terus bergerak, tapi prinsip senantiasa dinyala teguh.
Koskow 30 Maret 2022
Catatan: Sesi acara yang saya ikuti dalam gelaran ulang tahun ke-15 DGI yakni sesi obrolan santai. Apa yang saya tulis malah terkesan serius. Untung ada topik desain plesetanala Jogja. Lagi-lagi, bagi saya plesetanjuga serius. Sepertinya sayalah yang perlu santai. Kesimpulan: Semoga ada rubrik hahahihi atau semacamnya di situs DGI karena otokritik serta tawa juga sebentuk citarasa.
Quoted
Make your interactions with people transformational, not just transactional.

